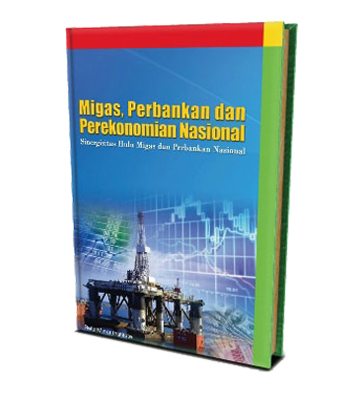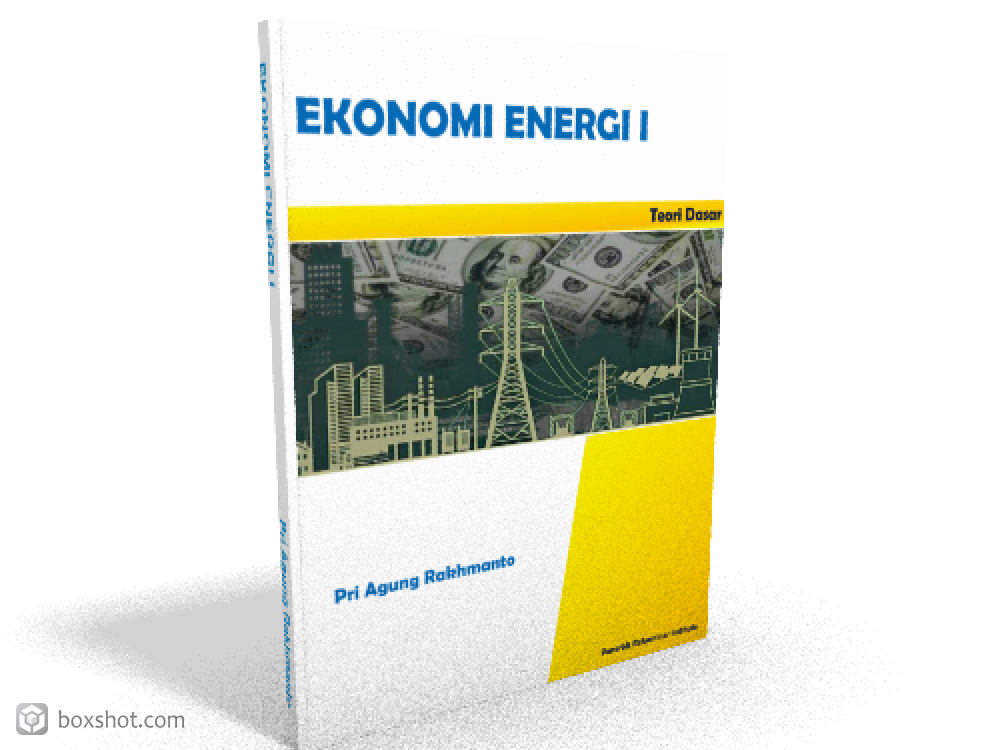Investordaily, 30 November 2020
Jakarta – Menipisnya margin bisnis gas bumi dinilai bakal menjadi ancaman bagi pembangunan infratruktur gas bumi. Dengan terbatasnya cadangan minyak, sementara cadangan gas masih sangat melimpah, infrastruktur gas sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Komaidi Notonegoro, pengamat energi dari Reforminer Institute mengatakan, dengan kondisi harga gas yang murah dan diikuti oleh adanya ketidakjelasan pasar, akan membuat tingkat Return of Investment (RoI) dari sebuah proyek pembangunan infrastruktur gas bumi menjadi lama.
“Semakin rendah harga gas, semakin tipis margin yang bisa didapat pengembang. Ini yang akan menyulitkan pelaku usaha sulit membangun infrastruktur baru,” katanya di Jakarta dalam pernyataannya yang diterima redaksi, Minggu (29/11).
Menurutnya penurunan harga gas di tengah masa pandemi belum memberikan dampak signifikan bagi industri pengguna. Sebab, penurunan harga gas itu ikut tidak mendongkrak volume produksi maupun penjualan industri pengguna gas yang saat ini tengah menghadapi pelemahan pasar.
“Tujuan penurunan harga gas memang baik bagi industri, tapi momentumnya tidak tepat,” kata Komaidi.
Menurutnya, penurunan harga gas yang diinisiasi pemerintah lewat Kementerian ESDM sangat terburu-buru. Kebijakan ini terkesan hanya untuk memenuhi peraturan yang sudah lama dibuat tapi tidak kunjung terlaksana. Sebelumnya, kata Komaidi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Dalam Perpres tersebut, pemerintah menetapkan harga gas bumi yang sebelumnya US$ 7 per Million British Termal Unit (MMBTU) diturunkan menjadi US$ 6 per MMBTU. Pada 6 April 2020 Menteri ESDM merilis Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
Pasal 3 ayat 1 peraturan itu mengatur harga gas bumi tertentu di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) ditetapkan sebesar US$ 6 per MMBTU. Ada tujuh sektor industri yang dapat harga khusus dari kebijakan tersebut, yakni industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan industri sarung tangan karet. Sebagai dampak kebijakan itu pemerintah merelakan jatahnya dari penjualan migas di hulu dipangkas sekitar US$ 2 per MMBTU.
Kebijakan pemerintah memangkas harga gas bumi untuk industri tertentu di level US$ 6 per MMBTU memang jadi bumerang jika tidak didukung insentif bagi pengembang infrastruktur gas bumi. Karena dengan margin yang terbatas, perusahaan akan lebih memilih risiko terendah, yaitu mengelola infrastruktur yang sudah jelas pasokan dan pasarnya.
Masih menurut Komaidi, akan sangat berat jika memaksa perusahaan yang marginnya dipangkas oleh kebijakan pemerintah untuk membangun infrastruktur gas bumi. Kecuali ada insentif yang memberikan solusi bagi pengembang infrastruktur bahwa bisnis mereka tetap sehat ketika ekspansi,” tegas Komaidi.
“Kalau investor melihat investasi di tempat lain, misalnya, bisa dapat IRR 12%, sementara di infrastruktur gas bumi IRR nya lebih rendah, maka tidak akan ada investor yang mau berinvestasi untuk mengembangkan infrastruktur gas,” ujarnya.
Dengan melambatnya pengembangan infrastruktur gas, pada akhirnya target pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik sulit terealisasi karena infrastrukturnya tidak tumbuh
Pembangunan infrastruktur gas bumi memang memiliki risiko yang besar. Selain faktor ketersediaan pasokan, penyerapan gas oleh konsumen juga menjadi risiko bagi pengembang infrastruktur gas bumi. Sementara biaya pembangunan infrastruktur gas sangat mahal.
Banyak infrastruktur gas yang telah dibangun gagal dioptimalkan karena tidak adanya pasokan dan pasar yang seimbang. Yang terjadi kemudian pengembang infrastruktur gas harus menanggung biaya yang mahal. Kondisi ini yang membuat sedikit sekali perusahaan swasta yang mau membangun infrastruktur gas bumi.
Di sisi lain kebijakan harga gas US$ 6 terbukti menguntungkan sejumlah perusahaan swasta. Perusahaan keramik yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI)melaporkan kenaikan laba bersihnya sejak harga baru gas bumi itu diterapkan.
Laba bersih PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) pada kuartal III 2020 melesat 38,31% menjadi Rp 221,5 miliar dibandingkan periode sama 2019. Kenaikan laba itu terjadi di saat pendapatan turun 1,1% menjadi Rp 1,61 triliun. Pengatrol utamanya adalah terpangkasnya beban pokok penjualan sebesar 6,6% jadi Rp 1,12 triliun.

Katadata.co.id; 26 November 2020
Oleh: Komaidi Notonegoro
Dari aspek moneter, proyek gasifikasi batu bara akan memangkas impor LPG sehingga mengurangi tekanan defisit neraca dagang. Namun dari aspek fiskal berpotensi membebani anggaran negara dalam APBN.
Pemerintah menetapkan kebijakan gasifikasi batu bara untuk mengurangi impor LPG yang terus meningkat setiap tahun. Data Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia menunjukkan impor Elpiji ini meningkat dari kisaran 917 ribu ton pada 2009 menjadi sekitar 5,71 juta ton pada 2019.
Proyek gasifikasi batu bara yang mengubah batubara menjadi dimethyl ether (DME) diharapkan dapat mensubstitusi dan sekaligus mengurangi impor LPG. Berdasarkan catatan, pengembangan proyek DME sudah direncanakan cukup lama. Kebijakan pengembangan DME tercatat telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
RUEN tersebut menargetkan pada 2025 produksi DME Indonesia satu juta ton. Produksi DME ditargetkan meningkat menjadi 1,2 juta ton pada 2030, 1,5 juta ton pada 2040, dan 1,9 juta ton pada 2050.
Dewan Energi Nasional (DEN) justru lebih optimistis dari target yang ditetapkan dalam RUEN tersebut. DEN menginformasikan bahwa pada 2025 mendatang komitmen produksi DME yang akan dilakukan oleh tiga badan usaha yaitu PT Bukit Asam, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin Indonesia adalah sekitar 6 juta ton.
Nilai Keekonomian Proyek
Salah satu proyek DME yang saat ini diinformasikan mulai berjalan adalah proyek kerjasama PT Bukit Asam – PT Pertamina – Air Product yang berlokasi di Tanjung Enim Sumatera Selatan. Proyek tersebut direncanakan Commercial Operation Date (COD) pada 2025 dan saat ini sedang pada tahap penyelesaian feasible study dan skema bisnis.
Meskipun proyek DME dinilai memenuhi aspek kelayakan teknis, pemerintah dan pelaksana proyek DME perlu lebih cermat dan hati-hati di dalam menghitung kelayakan ekonominya. Sejumlah kajian menyebutkan bahwa nilai keekonomian proyek DME relatif rendah dan tidak cukup ekonomis sebagai pengganti LPG. Keenonomian proyek yang relatif rendah disinyalir sebagai penyebab sejumlah proyek DME di sejumlah negara relatif belum berkembang dengan baik.
Berdasarkan informasi dari International DME Association (IDA), sampai saat ini terdapat 10 negara yang merencanakan dan melaksanakan proyek DME. Di antaranya adalah Cina, Swedia, India, Uzbekistan, Jepang, Amerika Serikat, Trinidad & Tobago, Pepua New Guenia, Vietnam, dan Indonesia.
Data yang ada menunjukkan saat ini potensi pasar terbesar DME adalah Cina. Kapasitas terpasang kilang DME di sana sekitar tujuh juta matrik ton (MT) per tahun. Dari total kapasitas terpasang tersebut, tingkat utilitasnya diinformasikan hanya 30 – 50 %. Bahkan untuk kilang DME yang dibangun di wilayah Xinjiang, Qinhai, Ningkia, dan Shaannxi tingkat utilitasnya diinformasikan di bawah 30 % dari total kapasitas terpasangnya.
Tingkat utilitas kilang DME di Cina yang relatif rendah tersebut diinformasikan karena nilai keekonomian proyek yang relatif rendah. Informasi yang ada menyebutkan lebih dari 80 % produksi DME di Cina digunakan untuk proses blending dengan LPG (20 % DME:80 % LPG). Karena itu nilai keekonomian proyek DME semakin rendah sejalan dengan harga LPG di pasar internasional yang sedang turun.
Khusus untuk proyek DME di Indonesia, kajian Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) yang dipublikasikan pada November 2020 menyebutkan bahwa rencana proyek DME yang akan dilaksanakan PT Bukit Asam – PT Pertamina – Air Product tidak cukup ekonomis dan berpotensi merugi. Bahkan IEEFA dalam hal ini menyebut proyek DME di Indonesia sebagai (D)oes Not (M)ake (E)conomic Sense.
Dalam menghitung proyek DME yang akan dilaksanakan PT Bukit Asam – PT Pertamina – Air Product, IEEFA menggunakan beberapa asumsi dasar, di antaranya: (1) kebutuhan investasi proyek DME sebesar US$ 2 miliar; (2) kapasitas produksi kilang DME 1,4 juta MT per tahun dan menggunakan 6,5 juta ton batu bara per tahun, serta untuk menggantikan impor LPG 980.000 ton per tahun; (3) kebutuhan investasi dipenuhi dari utang dengan biaya bunga sekitar 3,8 % per tahun, dan (4) menggunakan acuan rata-rata biaya produksi DME perusahaan Lanhua yaitu listed company di Cina selama periode 2016-2019.
Berdasarkan sejumlah asumsi dasar tersebut, IEEFA memproyeksikan proyek DME yang akan dilaksanakan oleh PT Bukit Asam – PT Pertamina – Air Product akan merugi sekitar US$ 377 juta per tahun atau sekitar Rp 5,35 trilun per tahun jika mengacu pada nilai tukar rupiah pada saat tulisan ini dibuat. IEEFA menyebutkan, jika manfaat ekonomi dari pengurangan impor LPG diperhitungkan, masih terdapat kerugian sekitar US$ 18,9 juta atau sekitar Rp 269 miliar untuk setiap tahunnya dari proyek DME tersebut.
Mengacu pada sejumlah informasi yang ada tersebut, PT Bukit Asam, PT Pertamina, Air Product, dan Pemerintah Indonesia perlu lebih cermat dan berhati-hati di dalam melaksanakan proyek DME. Dari aspek moneter, sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa pelaknaan proyek DME akan memberikan dampak positif. Pelaksanaan proyek DME secara otomatis akan mengurangi besaran impor LPG yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama penyebab defisit neraca perdagangan migas.
Akan tetapi, jika ditinjau dari aspek fiskal dan mengacu pada proyeksi IEEFA tersebut, pelaksanaan proyek DME berpotensi memberikan risiko terhadap keuangan negara atau akan menjadi beban dalam APBN. Jika konsisten dengan ketentuan UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, kerugian dalam proyek DME yang merupakan bagian dari pelaksanaan program pemerintah harus diberikan subsidi oleh negara c.q pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tidak dapat membebankan kerugian kepada badan usaha sebagai pelaksananya meskipun pelaksana penugasan tersebut adalah BUMN.
Berdasarkan sejumlah kondisi yang ada, terdapat potensi biaya dan manfaat dalam pelaksanaan proyek DME. Karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terutama untuk menghitung biaya dan manfaat dari proyek DME yang akan dilaksanakan. Hasil kajian atau perhitungan pemerintah tentu dapat berbeda dengan hasil kajian IEEFA tersebut.
Dalam hal ini IEEFA hanya melihat berdasarkan aspek bisnis, sementara pemerintah tentu harus lebih komprehensif tidak semata-mata perhitungan bisnis tetapi juga harus mengakomodasi aspek lain seperti aspek keberlanjutan dan ketahanan energi nasional. Bahwa di dalam melakukan kajian IEEFA memiliki motif atau interest yang lain juga sangat dimungkinkan.
Akan tetapi dalam menyikapi hasil kajian IEEFA tersebut, kita perlu positif di dalam melihatnya bahwa hal tersebut merupakan pengingat begi kita semua bahwa memang benar sebuah program atau proyek akan dapat berkelanjutan jika dilaksanakan berdasarkan basis yang jelas dan kuat.

Tribunbisnis.com; 21 November 2020
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menegaskan, bahwa rencana penghapusan Premium merupakan kewenangan Pemerintah.
Dan upaya tersebut, membutuhkan komitmen dan kesepakatan bersama. “Teman-teman KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berada di barisan paling depan. Tetapi, yang punya hajat kan tidak hanya KLHK, namun ada juga Kementerian ESDM,†kata Komaidi pada acara seminar online yang diadakan Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) hari ini.
Untuk itulah, maka menurut ReforMiner, solusinya adalah satu kata, satu perbuatan. Dalam hal ini, Pemerintah harus konsisten. Silakan jika Premium harus dihilangkan, tetapi harus disusun roadmap secara bertahap agar diterima masyarakat.
Baca juga:Â Konsumsi Pertalite Melebihi Penjualan Premium, tapi Banyak yang Gagal Paham
“Masyarakat kita ini masyakat yang paternalistik. Masyarakat juga nerimo ing pandum. Jika Premium tidak ada, dan hanya ada Pertalite, maka ngedumel hanya 1-2 bulan. Setelah itu, kondisi berjalan normal karena mau tidak mau, harus mempergunakan BBM,†kata Komaidi.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mendukung penuh upaya peningkatan kualitas udara melalui bahan bakar minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan.
Termasuk di antaranya, jika Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan penghapusan BBM jenis Premium.
“Kami sangat mendukung. Bahkan Pemkab juga sudah melaksanakan Program Langit Biru sejak 2010,†kata Sekretaris Bappeda Gunung Kidul Sri Agus Wahyono pada acara yang sama.
Sementara terkait upaya peningkatan udara bersih pada tahun ini, lanjut Sri Agus, Pemkab Gunung Kidul juga memiliki beberapa kebijakan. Antara lain, melarang hampir semua SPBU menjual Premium. “Jadi yang boleh dijual adalah BBM jenis Pertalite dan Pertamax,†kata Sri Agus.
Kalau pun masih ada dua SPBU yang diperbolehkan menjual Premium, maka diizinkan pada waktu tertentu saja, yaitu pagi dan sore hari. Sedangkan untuk waktu di luar itu, kedua SPBU itu pun hanya boleh menjual BBM dengan oktan yang lebih tinggi.
Salah satu alasan, bahwa kedua SPBU masih diizinkan menjual Premium dalam waktu tertentu, karena BBM jenis tersebut masih dibutuhkan nelayan.
“Mereka masih tergantung Premium. Karena jika membeli Pertamax, tentu kesulitan dalam biaya operasional,†lanjut Sri Agus.
Begitupun, Sri Agus tidak menepis bahwa Pemda Gunung Kidul terus mendorong, jika ada kebijakan untuk penggunaan BBM dengan oktan lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas udara.
Termasuk tidak menutup kemungkinan, Pertalite sebagai BBM alternatif bagi nelayan.
Tetapi untuk itu, jelasnya, upaya tersebut bisa dipercepat jika dibarengi dengan penurunan harga Pertalite menjadi setara Premium. Paling tidak, dengan harga yang cukup mendekati.
“Marilah kita hilangkan Premium. Kita semua paling tidak menggunakan Pertalite, tetapi harganya hendaknya disamakan. Pekara nanti dinaikkan lagi tidak apa-apa, yang penting di awal ini, hendaknya harga disamakan,†ujarnya.
Kalau hal itu dilakukan, tentu menggairahkan masyarakat. Dan penurunan harga tersebut merupakan solusi paling relevan dan paling logis untuk kondisi faktual saat ini.
“Yang penting, jangan ada kebijakan ‘bolak-balik’ (tidak konsisten). Sekarang Premium tidak boleh, besok boleh. Itu sangat mengganggu kelangsungan SPBU,†kata Sri Agus.

Investor.id; 20 November 2020
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute dan Pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti
Rencana kebijakan penghapusan BBM RON rendah, yaitu bensin RON 88 atau dalam merek dagang lebih dikenal sebagai Premium, ramai diperbincangkan. Sejumlah informasi menyebutkan pemerintah berencana tidak lagi menyediakan Premium di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) efektif mulai 1 Januari 2021 mendatang. Meskipun sudah ramai menjadi diskusi publik, berdasarkan pencermatan, pemerin tah tampak belum sepenuhnya satu suara terkait rencana kebijakan tersebut.
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK menyampaikan telah bertemu Direktur Operasi PT Pertamina (Persero) dan menyebutkan bahwa per 1 Januari 2021 Pertamina akan meniadakan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.
Sementara itu, Dirjen Migas yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut menyampaikan belum bertemu dan berkoordinasi dengan pihak KLHK.
Kewenangan Kebijakan
Berdasarkan ketentuan UU Minyak dan Gas Bumi maupun aturan pelaksanaannya yang di antaranya Perpres No 191/2014 j.o Perpres No.43/2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, kewenangan penyediaan dan pendistribusian BBM termasuk kewenangan meniadakan jenis BBM tertentu melekat pada pemerintah.
Sementara itu, Pertamina dan badan usaha yang lain hanya berperan sebagai pelaksana penugasan dan/atau pelaksana PSO yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengacu pada ketentuan tersebut, pelaksanaan penghapusan BBM jenis Premium sepenuhnya akan ditentukan oleh konsistensi pemerintah di dalam melaksanakan rencana kebijakan yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan rekam jejak, pemerintah tidak cukup konsisten di dalam melaksanakankebijakan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis Premium.
Melalui ketentuan pasal 3 ayat (3) Perpres No 191/2014, pemerintah menetapkan bahwa sejak 31 Desember 2014 BBM jenis Premium tidak lagi didistribusikan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Akibat kebijakan tersebut, pemerintah berhasil mengurangi konsumsi BBM jenis Premium dari 29,70 juta KL pada 2014 menjadi sekitar 7 juta KL pada 2017.
Akan tetapi, ketika konsumsi telah berhasil diturunkan, justru sejak 24 Mei 2018 melalui Perpres No 43/2018 pemerintah kembali menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Akibatnya, konsumsi BBM jenis Premium yang sudah sempat menurun menjadi sekitar 7 juta KL pada 2017 kembali meningkat menjadi sekitar 12 juta KL pada 2019. Konsumsi Premium berpotensi terus meningkat jika permintaan penambahan kuota yang disampaikan oleh sejumlah wilayah dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Rencana penghapusan BBM jenis Premium pada dasarnya memiliki basis yang cukup kuat. Penggunaan BBM Premium yang notabene sebagai bensin RON 88 tidak memenuhi ketentuan regulasi di bidang lingkungan, yaitu Permen KLHK No P20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O. Ketentuan pasal 3 ayat (2) Permen KLHK tersebut menetapkan bahwa BBM jenis bensin yang diperbolehkan untuk digunakan adalah minimal memiliki RON 91. Ditinjau dari aspek penggunanya, saat ini jumlah negara yang menggunakan BBM jenis RON 88 semakin sedikit.
Berdasarkan data, saat ini hanya ada 7 negara yang menggunakan BBM RON 88, yaitu Bangladesh, Uzbekistan, Ukraina, Mongolia, Colombia, Mesir, dan Indonesia. Negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Singapura sudah sejak lama tidak menggunakan BBM RON 88, bahkan mereka sudah cukup lama menggunakan BBM dengan RON minimal 91.
Relatif terbatasnya jumlah Negara yang menggunakan BBM RON 88 menyebabkan ketersediaan data BBM jenis tersebut relative terbatas. Dampaknya, pengguna BBM RON 88 tidak memiliki basis data dan informasi yang cukup mengenai harga BBM RON 88 yang dapat digunakan sebagai referensi di dalam proses pengadaannya.
Ketika harga referensi sebuah produk relatif terbatas, maka potensi penyimpangan dalam proses pengadaannya semakin besar. Karena itu, penghapusan Premium berpotensi dapat meningkatkan aspek transparansi dalam proses pengadaan BBM di Indonesia.
Penghapusan BBM jenis Premium juga dapat mendorong kebijakan pengelolaan dan pengusahaan BBM di Indonesia menjadi lebih baik. Pemisahan administrasi negara dan administrasi usaha yang dijalankan oleh pelaksana penugasan dapat dilakukan dengan lebih baik. Berdasarkan ketentuan Perpres No 191/2014 j.o Perpres No 43/2018, BBM RON 88 atau Premium ditetapkan sebagai BBM Khusus Penugasan.
Dalam hal ini BBM Khusus Penugasan adalah BBM yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Ketentuan “tidak diberikan subsidi†tersebut menjadi pintu masuk tercampurnya administrasi Negara dan administrasi usaha. Dalam implementasinya, meskipun tidak lagi diberikan subsidi, pelaksana penugasan BBM RON 88 tidak diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan harga seperti kewenangan di dalam menetapkan harga BBM non-subsidi.
Kebijakan penetapan harga BBM Khusus Penugasan tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam tingkatan ter tentu, meskipun pelaksana penugasan diberikan ruang untuk dapat mengusulkan besaran harga, persetujuan dan penetapan harga BBM Khusus Penugasan tetap berada di tangan pemerintah.
Dalam implementasinya, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, pemerintah seringkali menetapkan harga jual BBM Khusus Penugasan di bawah harga keekonomiannya. Karena tidak lagi diberikan subsidi, selisih harga penetapan dan harga keekonomian dari BBM Khusus Penugasan dibebankan kepada pelaksana penugasan (Pertamina).
Dalam hal ini selisih harga yang berdasarkan ketentuan UU Keuangan Negara seharusnya diberikan subsidi dan menjadi beban negara (pemerintah) kemudian digeser menjadi beban pelaksana penugasan.
Berdasarkan sejumlah permasalahan yang ada tersebut, rencana kebijakan penghapusan BBM RON rendah (BBM jenis Premium) dapat berpotensi memberikan dampak positif tidak hanya terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup tetapi juga positif terhadap kebijakan pengelolaan dan pengusahaan BBM.
Dalam hal ini, yang tidak kalah penting dari semua itu adalah konsistensi pemerintah di dalam melaksanakan rencana kebijakan yang telah ditetapkan. Inkonsistensi kebijakan penyediaan dan pendistribusian BBM RON 88, seperti dalam contoh kasus re visi Perpres No 191/2014 dengan Perpres No 43/2018, justru menim bulkan ketidakpastian di dalam kegiatan usaha penyediaan BBM, memunculkan biaya tambahan dalam penyediaan BBM, dan dapat menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Kompas.com; 17 November 2020
Revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional 2021. Hal ini membuat iklim usaha hulu migas di Indonesia masih dibayangi ketidakpastian.
KOMPAS — Nasib investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia masih tak menentu menyusul tidak dimasukkannya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Program Legislasi Nasional 2021. Pembahasan sektor ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap belum cukup. Hal krusial yang butuh kejelasan adalah status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta mengenai izin usaha.
Dalam rapat panitia kerja penyusunan program legislasi nasional rancangan undang-undang (RUU) prioritas 2021 oleh Badan Legislasi DPR, Selasa (17/11/2020), terdapat 37 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Di sektor energi, hanya ada satu RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan yang masuk dalam daftar Prolegnas. Perubahan UU No 22/2001 yang disebut-sebut masuk dalam Prolegnas 2021 justru tidak ada.
â€Tidak semua usulan dapat masuk dalam Prolegnas RUU prioritas 2021 mengingat capaian legislasi masih sangat rendah dan program legislasi yang sudah ditetapkan,†ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya saat membuka rapat tersebut.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, tidak masuknya perubahan UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Prolegnas 2021 membuat pelaku industri hulu migas hilang kepercayaan pada pemerintah. Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa hal-hal yang tidak tercantum dalam UU Cipta Kerja untuk sektor migas akan dibahas dalam revisi UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Dengan tidak masuknya perubahan UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Prolegnas 2021 kian membuat pelaku industri hulu migas hilang kepercayaan pada pemerintah.”
Selain itu, sektor migas yang juga diatur dalam UU Cipta Kerja belum memberikan kejelasan dan kepastian. Contohnya adalah status kegiatan usaha migas yang diganti dengan sistem perizinan. Lalu, bagaimana nasib kontrak bagi hasil yang sudah berjalan sekarang ini? Tidak ada penjelasan sama sekali,†kata Komaidi.
Dalam UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Pasal 40 yang mengatur tentang perubahan UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan di Pasal 5 bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasar perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kegiatan usaha tersebut menyangkut wilayah hulu (eksplorasi dan eksploitasi) serta hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga).
â€Kalau sifatnya izin usaha kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lalu bagaimana nasib Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)? Sama sekali tidak ada dalam bab penjelasan,†kata Komaidi.
Hal yang sama disampaikan Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho. Menurut dia, berbagai persoalan di sektor hulu migas Indonesia sangat mendesak untuk dituntaskan, seperti nasib kelembagaan SKK Migas dan Indonesia yang kini berstatus net importer minyak sejak 2004. Belum pula masalah terus menipisnya cadangan minyak nasional dan aspek tata kelola.
â€RUU No 22/2001 diharapkan dapat menyelesaikan persoalan terkait ketidakpastian hukum setelah diundangkannya UU Cipta Kerja, khususnya yang menyangkut izin usaha hulu migas,†ujar Aryanto.

Sindonews.com; 17 November 2020
Komaidi Notonegoro
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti
DALAMÂ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sektor batubara tercatat diberi perhatian khusus. Terhadap UU Mineral dan Batubara Nomor 4/2009 jo UU Nomor 3/2020, UU Cipta Kerja hanya menyisipkan satu pasal, yaitu Pasal 128A di antara Pasal 128 dan Pasal 129, serta mengubah ketentuan Pasal 162.
Substansi dari Pasal 128A adalah memberikan insentif bagi pengusahaan batubara. Dalam hal ini kegiatan usaha batubara diberikan perlakuan khusus terhadap kewajiban penerimaan negara. Untuk pelaku usaha di sektor batubara yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara akan dibebaskan dari kewajiban membayar royalti. Adapun substansi dari Pasal 162 adalah mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), atau surat izin penambangan batuan (SIPB).
Substansi Perubahan
Secara keseluruhan saya menilai perubahan, penghapusan, dan penambahan ketentuan UU Mineral dan Batubara di dalam UU Cipta Kerja relatif tidak begitu banyak karena substansi dari UU Nomor 3/2020 tersebut telah sesuai dengan roh dan prinsip dari UU Cipta Kerja itu sendiri. Jika melihat tata waktu pengundangannya, menjadi cukup logis jika UU Nomor 3/2020 yang diundangkan pada 10 Juni 2020 telah memiliki kesesuaian dengan UU Nomor 11/2020 yang diundangkan pada 2 November 2020.
Dalam perspektif makroekonomi dan keuangan negara, pemberian perlakuan khusus kepada sektor batubara melalui UU Cipta Kerja tersebut relatif dapat dipahami. Berdasarkan perkembangan yang ada, kontribusi sektor batubara terhadap penerimaan negara, perolehan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pembentukan PDB nasional mengalami peningkatan. Hal tersebut kemungkinan yang menjadi basis pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap sektor batubara.
Berdasarkan kondisi yang ada, peran sektor batubara terhadap perekonomian nasional untuk beberapa tahun ke depan kemungkinan semakin meningkat. Struktur perekonomian Indonesia yang saat ini lebih banyak dikontribusikan oleh sektor-sektor ekonomi yang padat energi—khususnya listrik—kemungkinan akan mengalami penurunan produktivitas dan daya saing jika kegiatan sektor batubara terganggu.
Pada tingkatan tertentu kemudahan dalam akses tenaga listrik, termasuk biaya pemanfaatannya, akan menjadi penentu tingkat produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Hal tersebut karena porsi biaya listrik dalam struktur biaya produksi sektor industri manufaktur dan jasa-jasa yang notabene sebagai kontributor utama pembentuk PDB Indonesia cukup signifikan. Karena itu, jika biaya produksi listrik dapat lebih murah maka potensi peningkatan daya saing dan produktivitas perekonomian nasional juga semakin besar. Kondisi yang ada tersebut kemungkinan yang menyebabkan mengapa sebagian besar pembangkit listrik nasional saat ini menggunakan batubara. Hal itu karena jika dibandingkan dengan sumber energi fosil yang lain, batubara tercatat sebagai sumber energi primer pembangkit yang paling murah.
Statistik PLN 2019 menyebutkan bahwa rata-rata biaya operasi yang meliputi biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan, penyusutan, beban bunga, biaya pegawai, dan biaya lain-lain untuk pembangkit batubara (PLTU) sebesar Rp653,12 per kwh. Biaya tersebut lebih rendah dari rata-rata biaya operasi pembangkit yang menggunakan energi primer BBM (PTLD) sebesar Rp3.308,26 per kwh dan biaya operasi pembangkit yang menggunakan gas (PLTG) Rp2.570,03 per kwh.
Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar BBM dan gas, seluruh komponen biaya operasi untuk pembangkit PLTU pada 2019 tercatat lebih rendah. Untuk biaya energi primer atau bahan bakar, misalnya, rata-rata biaya yang diperlukan untuk memproduksi listrik dari batubara adalah Rp445,85 per kwh. Sementara rata-rata biaya bahan bakar yang diperlukan untuk memproduksikan listrik dari BBM dan gas pada tahun yang sama masing-masing Rp2.454,32 per kwh dan Rp1.908,93 per kwh.
Untuk 2019, rata-rata porsi biaya energi primer atau bahan bakar terhadap total biaya pembangkitan sekitar 75%. Berdasarkan porsi tersebut, penyediaan listrik dengan biaya bahan bakar yang lebih murah secara umum akan menghasilkan total biaya operasi penyediaan listrik yang lebih rendah. Dalam penyediaan listrik dari batubara, karena biaya bahan bakarnya relatif lebih murah dibandingkan energi fosil yang lain, maka secara keseluruhan biaya penyediaan listrik dari batubara juga menjadi lebih murah.
Dari sisi kapasitas, saat ini porsi kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan batubara sekitar 50% terhadap total kapasitas pembangkit yang ada. Porsi pembangkit listrik yang menggunakan batubara kemungkinan akan terus meningkat jika mengingat sebagian besar pembangkit listrik dalam proyek pembangkit listrik 35.000 MW adalah PLTU yang notabene menggunakan batubara sebagai energi primer pembangkit.
Kondisi eksisting pembangkit listrik nasional tersebut berpotensi mendorong konsumsi batubara domestik terus meningkat. Data menunjukkan, pada 2019 realisasi kebutuhan batubara untuk PLTU yang dioperasikan PLN saja sekitar 97,72 juta metrik ton. Jika mengacu pada RUPTL 2019-2028 kebutuhan batubara PLN diproyeksikan akan terus meningkat dan menjadi sekitar 152,63 juta metrik ton pada 2028. Kebutuhan batubara untuk kelistrikan nasional tentunya akan jauh lebih besar dari nilai tersebut jika mengingat PLTU tidak hanya dioperasikan oleh PLN, tetapi juga oleh pembangkit listrik non-PLN atau independent power producer (IPP).
Konsumsi batubara domestik juga berpotensi terus meningkat jika program gasifikasi batubara yang dilaksanakan pemerintah memenuhi nilai keekonomian dan berjalan dalam skala yang lebih masif. Sebagaimana diketahui, saat ini melalui kerja sama PT Bukit Asam dan PT Pertamina (Persero) pemerintah sedang melakukan gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) dan synthetic natural gas (SNG). Sejumlah kondisi yang ada tersebut kemungkinan yang menjadi basis pemerintah dan DPR memberikan perhatian khusus sektor batubara melalui UU Cipta Kerja.

Investor.id: Kamis,12 November 2020
Undang-Undang No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang proses revisinya menjadi inisiatif DPR dan telah berjalan selama 12 tahun menjadi bagian dalam UU Cipta Kerja. Dalam UU No 11/2020, perubahan, penghapusan, dan/ atau penambahan ketentuan baru dilakukan melalui pasal 40.
Berdasarkan review, terdapat delapan pasal UU No 22/2001 yang diubah melalui UU Cipta Kerja. Di antaranya pasal 1,4,5,23, 25,52,53, dan 55. Selain itu, UU Cipta Kerja menambahkan pasal 23A yang disisipkan antara pasal 23 dan pasal 24.
Beberapa perubahan yang dilakukan adalah definisi pemerintah pusat, definisi pemerintah daerah, pengaturan dalam kegiatan usaha hulu migas, pengaturan dalam kegiatan usaha hilir, dan tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Belum Memenuhi Ekspektasi
Berdasarkan review terhadap substansi pasal per pasal, saya menilai pengaturan klaster migas dalam UU Cipta Kerja masih belum memenuhi ekspektasi para stakeholder. Terutama ekspektasi pelaku usaha di sektor hulu migas.
Dalam tingkatan tertentu, beberapa pengaturan di dalam klaster migas justru dapat berpotensi menambah komplikasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Pasal-pasal UU No 22/2001 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan MK No 36/ PUU/X/2012 termasuk mengenai fungsi dan kedudukan BP Migas (sementara diganti SKK Migas) justru tidak diatur di dalam UU Cipta Kerja.
Sementara untuk hal yang dapat dikatakan tidak mendesak seperti mengubah sistem pengusahaan hulu migas dari kontrak kerja sama menjadi sistem perizinan justru dilakukan.
Berdasarkan pencermatan, dalam proses pembahasan sebelumnya terpantau terdapat pa salpasal dalam klaster migas yang mengakomodasi Keputusan MK No 36/PUU/X/2012 dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Bahkan pasal-pasal tersebut terpantau masih terdapat dalam draft RUU yang dibahas dan disetujui antara Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dan Fraksi-Fraksi di DPR pada 3 September 2020.
Di antara pasal-pasal klaster migas yang terpantau terdapat dalam draft RUU Cipta Kerja status 3 September 2020, namun kemudian tidak tertuang dalam UU No 11/2020 adalah pasal 4A, pasal 11, pasal 12, dan pasal 64A. Substansi pasal 4A adalah mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas, pembentukan BUMNK Hulu Migas, dan mekanisme kerja sama antara BUMNK Hulu Migas dengan Ba dan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam kegiatan usaha hulu migas.
Pasal 11 dan pasal 12 mengatur mekanisme dan tata cara dalam teknis pengusahaan hulu migas yang terkait dengan substansi pengaturan dalam pasal 4A.
Sementara itu, pasal 64A mengatur proses transisi dan pengalihan kewenangan dari SKK Migas kepada BUMNK Hulu Migas. Beberapa yang diatur adalah status kontrak kerja sama yang sedang berjalan dan kedudukan SKK Migas sebelum dan sesudah BUMNK Hulu Migas terbentuk.
Tidak munculnya sejumlah pasal dalam klaster migas UU No 11/2020 kemungkinan karena pemerintah c.q Kementerian ESDM mencabut ketentuan sejumlah pasal, termasuk pasal mengenai pembentukan BUMNK Hulu Migas. Keputusan tersebut konon diambil karena sejumlah ketentuan tersebut akan diatur dalam perubahan UU Minyak dan Gas Bumi No22/2001 yang akan masuk dalam Prolegnas.
Pencabutan ketentuan pasal 4A dari klaster migas UU Cipta Kerja pada dasarnya menyebabkan pengaturan Perizinan Berusaha dalam klaster migas menjadi tidak utuh dan rancu. Pada draft yang di sepakati 3 September 2020 saat itu ditetapkan bahwa “Pemerintah Pusat selaku pemegang Kuasa Pertambangan akan memberikan Perizinan Berusaha pada setiap Wilayah Kerja kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumiâ€.
Dalam bentuk yang berbeda, Perizinan Berusaha tersebut dapat dikatakan identik dengan Kuasa Usaha Pertambangan minyak dan gas yang diberikan kepada Per tamina melalui UU No 44 (Prp)/1960 dan UU No 8/1971. Ka rena itu pula, pada draft yang dise pakati sebelumnya ditetapkan bahwa nantinya kerja sama antara BUMNK Hulu Migas dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di dalam kegiatan usaha hulu migas akan dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
Karena itu, perubahan ketentuan sistem pengusahaan hulu migas dari kontrak kerja sama menjadi sistem perizinan menjadi rancu ketika BUMNK Hulu Migas tidak diatur di dalam klaster migas UU No 11/2020. Dapat muncul tafsir bahwa perizinan berusaha tersebut berlaku bagi seluruh pelaku usaha hulu migas, tidak hanya untuk BUMN tetapi juga untuk Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Konsekuensi dari ketentuan tersebut tidak sederhana, apalagi dalam klaster migas UU No 11/2020 tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai ketentuan peralihan.
Status kontrak kerja sama yang sedang berjalan, apakah harus disesuaikan atau tetap berlaku, belum diatur secara tegas. Tugas, fungsi, dan kedudukan SKK Migas ketika sistem kontrak kerja sama berubah menjadi perizinan juga belum diatur.
Mencermati perkembangan yang ada tersebut, saya menilai ketidakpastian terhadap substansi pengaturan payung hukum dalam kegiatan usaha minyak dan gas di Indonesia masih tetap tinggi karena mayoritas perubahan ketentuan UU Migas tetap akan dilakukan melalui revisi UU Migas No 22/2001.
Sejumlah perubahan, termasuk mun culnya ketentuan yang tidak sejalan dengan apa yang sudah tertuang dalam klaster migas UU No 11/2020 tersebut juga masih sangat berpeluang terjadi. Apalagi jika mencermati substansi draft RPP Sektor ESDM atas UU Cipta Kerja ya ng telah beredar ke public tidak terdapat pengaturan mengenai sektor minyak dan gas bumi di dalamnya.
*) Direktur Eksekutif ReforMiner Institute dan Pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti.