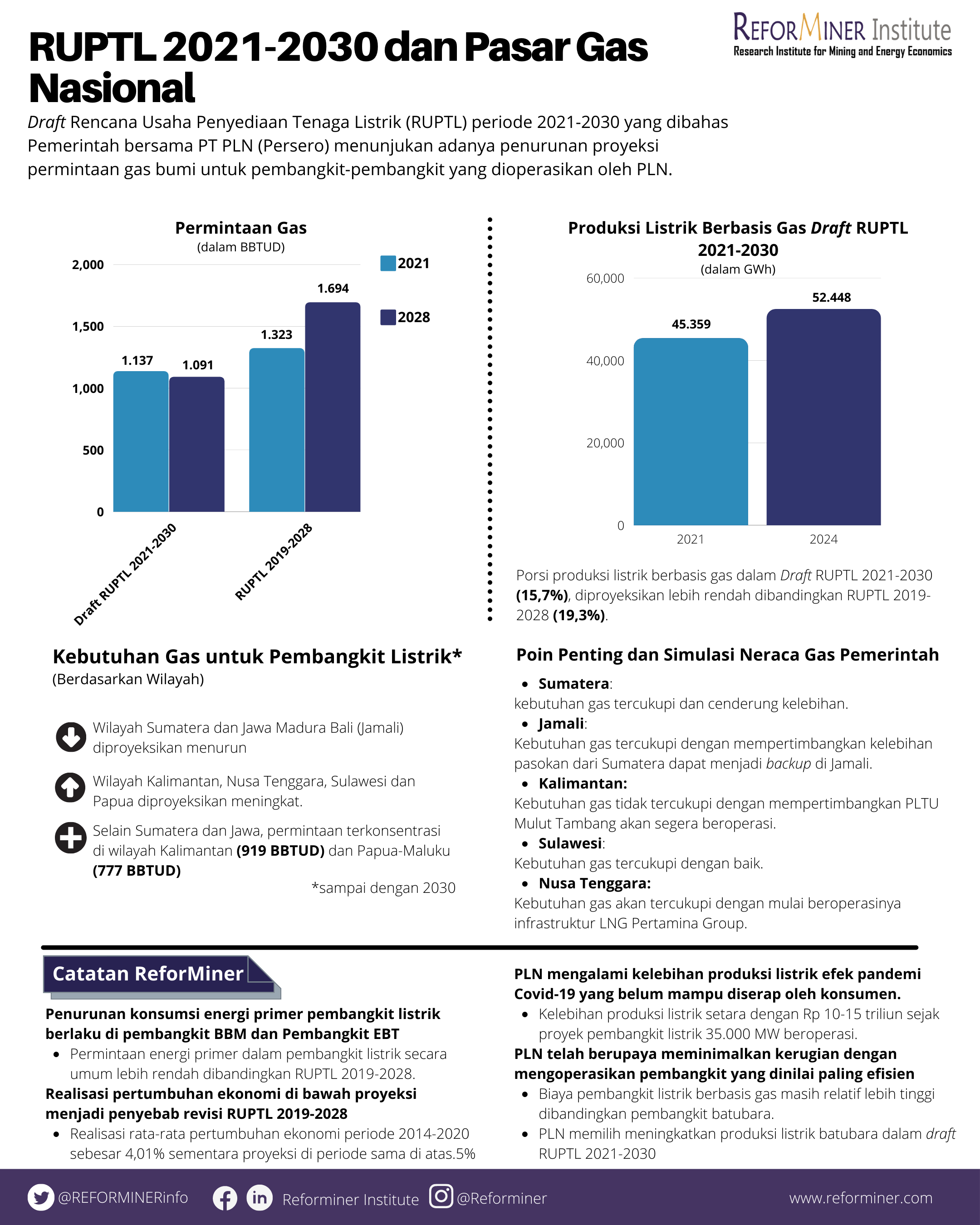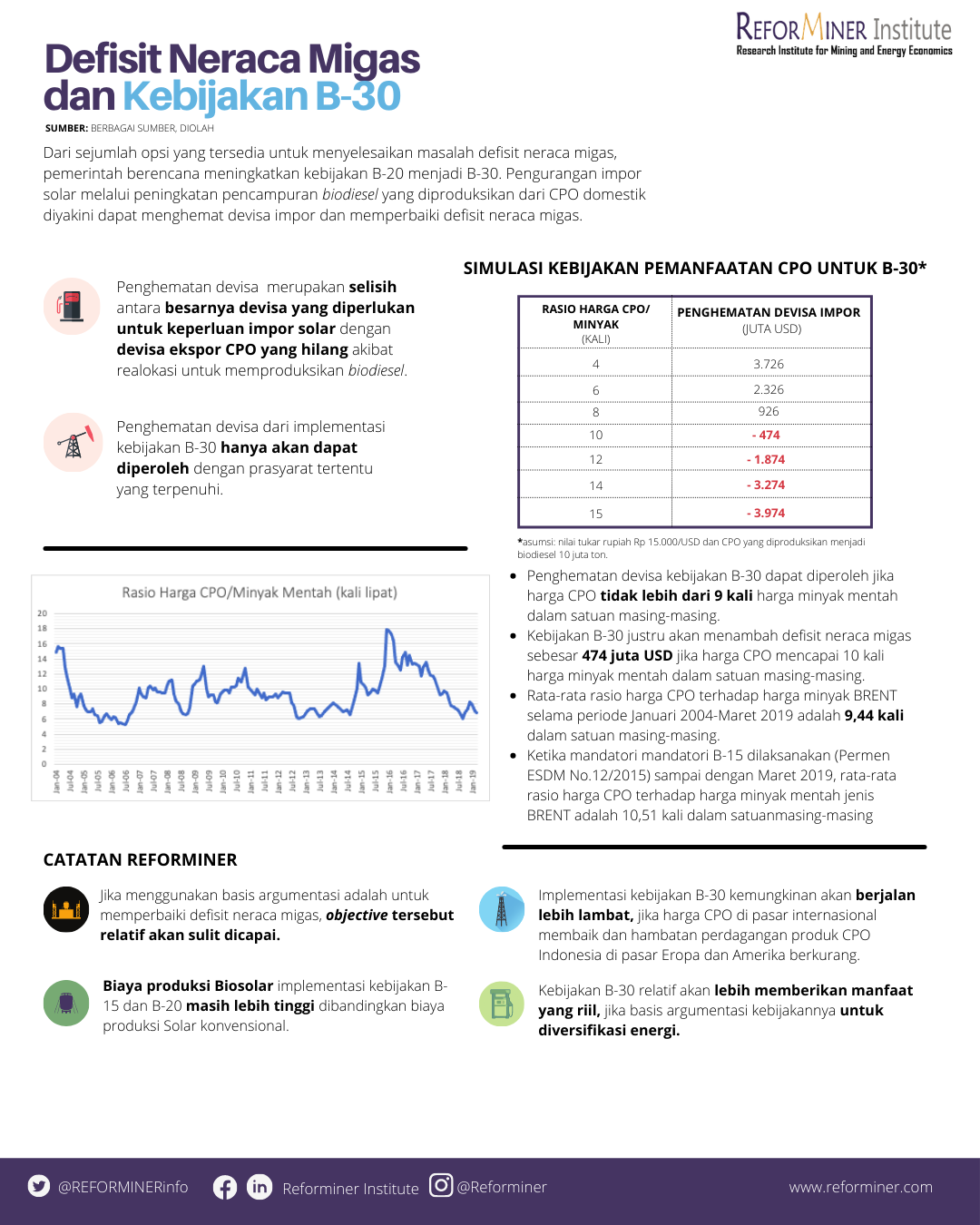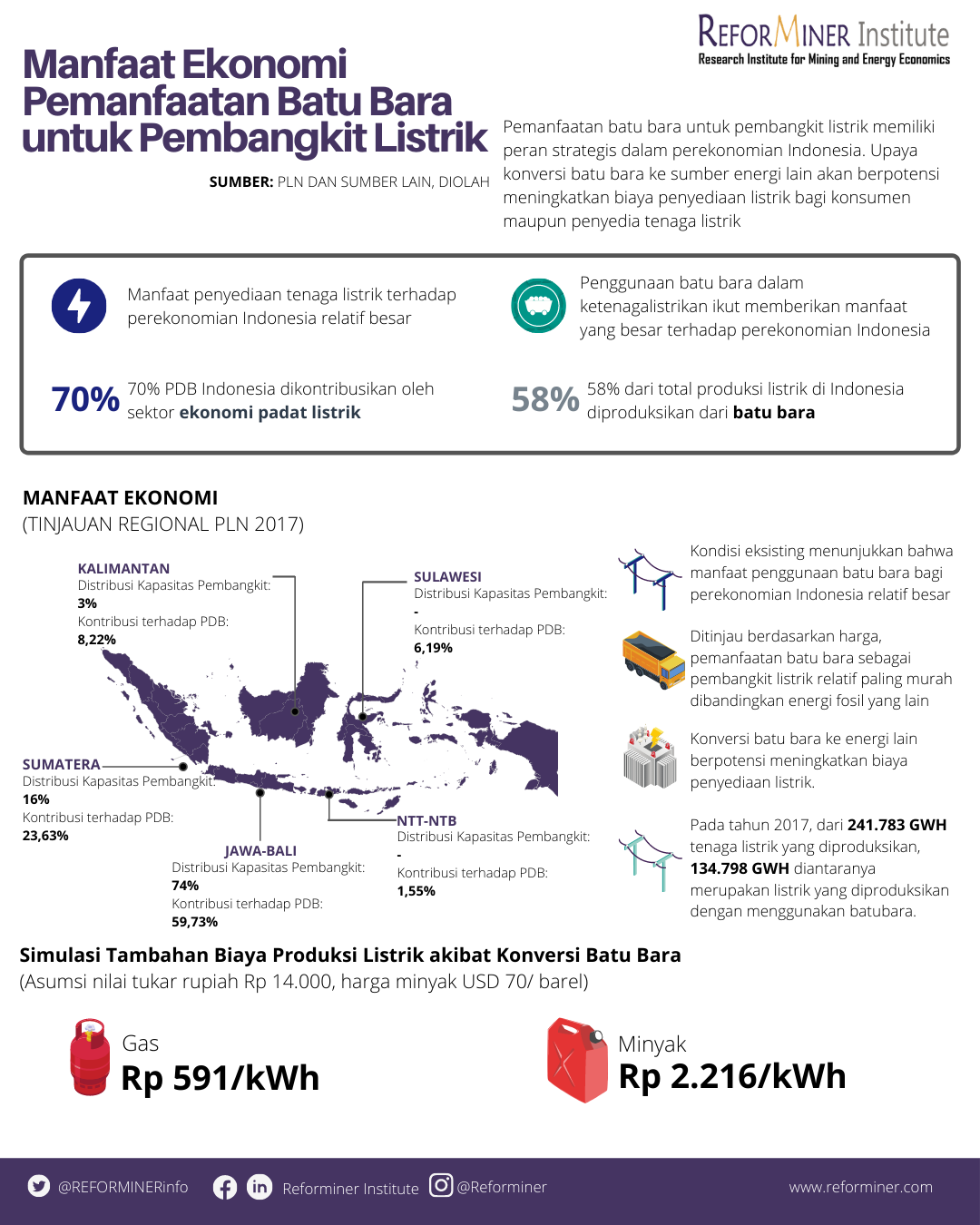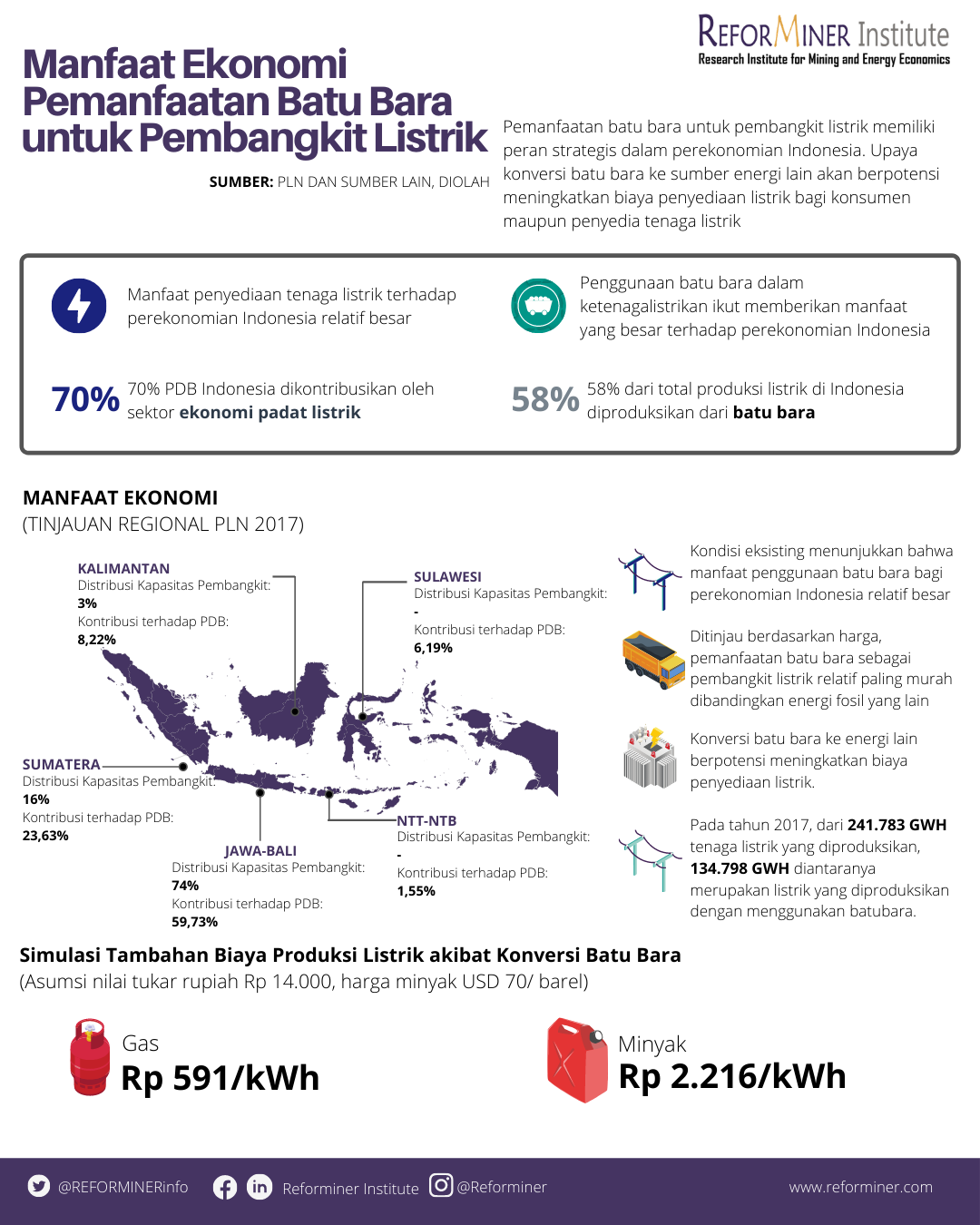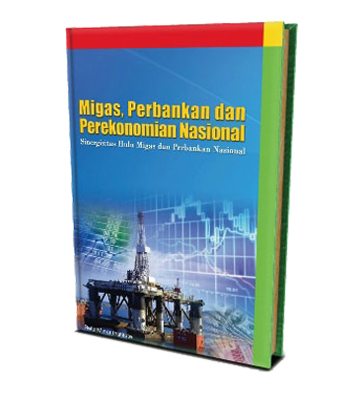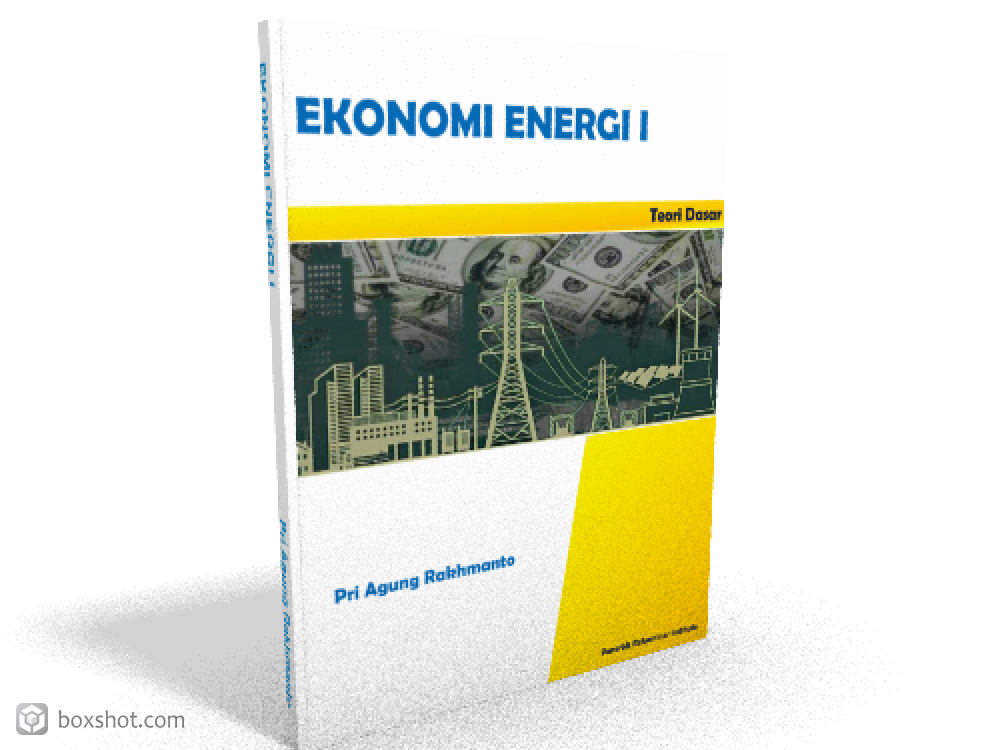Tribunnews.com; 26 Februari 2021
Produsen kendaraan bermotor, menjadi penentu penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas di masyarakat.
Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro mengatakan, upaya mendorong penggunaan BBM berkadar oktan atau RON di atas 91 perlu kerjasama semua pemangku kepentingan, terutama produsen kendaraan bermotor.
“Pabrikan kendaraan itu harus membuat kendaraan yang memang hanya bisa mengonsumsi BBM RON berkualitas. Kalau menggunakan BBM RON di bawah 91, katakanlah menjadi bermasalah mesinnya,” ujar Komaidi saat dihubungi, Jakarta, Senin (22/2/2021).
Untuk mencapai itu, kata Komaidi, pemerintah dapat melakukan intervensi kepada produsen kendaraan agar membuat mesin motor roda dua, maupun empat dengan BBM RON 91 ke atas.
“Pemerintah bisa menetapkan standar produksi, kalau sudah memenuhi target tertentu, baru diberikan izin. Kalau masih pakai RON di bawah 91, izinya jangan dikeluarkan,” papar Komaidi.
Jika hal tersebut berjalan, Komaidi meyakini Program Langit Biru yang digagas PT Pertamina (Persero) dalam penggunaan BBM berkuliatas, dapat berjalan maksimal.
“Kalau diserahkan ke masyarakat itu sulit, karena ketika masih ada pilihan untuk beli yang lebih murah, pasti akan memilih yang lebih murah, sepanjang kendaraannya masih bisa digunakan,” ujar Komaidi.
“Tapi kalau dari hulunya atau produsen kendaraan sudah mensetting mesin menggunakan BBM berkualitas, masyarakat tidak punya opsi, akhirnya memakai BBM RON 91 ke atas,” sambung Komaidi.
Komaidi khawatir jika Program Langit Biru tidak didukung dari hulu, Pertamina akan menurunkan kualitas produksi BBM di pasar.
“Pertamina sekarang sudah siap produksi BBM berkualitas, tapi kalau di pasar tidak ada yang beli, mereka akan rugi karena kalah di pasar, dan akhirnya menurunkan kualitas lagi, jual produk yang laku di pasar,” tutur Komaidi.

Katadata.co.id; 19 Februari 2021
Kementerian ESDM berencana mendorong pengembangan blok migas nonkonvensional dan akan menghadirkan kontrak kerja sama baru.
Pemerintah mempertimbangkan membuat kontrak kerja sama baru untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Usulan ini muncul dari para investor yang meminta adanya kontrak karya serupa dengan sektor pertambangan.
Dalam kontrak karya, sistem yang berlaku adalah pajak dan royalti. Sedangkan perjanjian kerja sama migas yang ada sekarang, baik itu cost recovery maupun gross split, merupakan bagian dari kontrak bagi hasil alias production sharing contract (PSC).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan soal ini. Kepala Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Komar Hutasoit mengatakan jenis kontrak baru yang tengah digodok tersebut diperuntukkan untuk blok migas non konvensional.
Supaya tidak kontradiktif dengan aturan Kementerian Keuangan, maka Kementerian ESDM masih melakukan koordinasi terkait mekanismenya. “Untuk bentuk kontrak baru masih harus menyesuaikan aturan, seperti undang-undang perpajakan,†katanya Indonesian Oil-Gas Outlook Webinar Series: Drilling & Exploration, Rabu (17/2).
Di sisi lain, blok migas nonkonvensional di Indonesia masih sangat baru. Secara teknis, pemerintah perlu melakukan kajian lebih dalam. Satu blok jenis ini yang berpotensi menghasilkan shale gas (gas serpih) ada di Sumatera Utara. “Tapi itu juga bukan sumur pengembangan,†ucap Komar.
Kementerian ESDM memang berencana mendorong pengembangan blok migas nonkonvensional. Salah satunya dengan fokus menggarap minyak serpih atau shale oil.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji sebelumnya mengatakan dalam pengembangan migas non konvensional pemerintah telah melakukan identifikasi potensi-potensinya. “Kami fokuskan ke shale oil,” ucap dia dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM.
Potensi minyak serpih di Indonesia, menurut dia, terbilang cukup besar. Apabila digarap dengan benar, maka target produksi satu juta barel minyak di 2030 dapat tercapai.
Hal yang sama juga pernah mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar katakan beberapa waktu silam. Potensi shale gas dan shale oil negara ini sangat besar tapi belum dimanfaatkan sama sekali. Sedangkan Amerika Serikat sudah melakukannya sejak 2007.
Produksi awalnya sekitar 4,5 juta barel minyak per hari (BOPD). Dalam waktu tujuh tahun, angkanya naik menjadi 9,5 juta barel minyak per hari. Berkat pengembangan blok nonkonvensional, kini negara adikuasa itu menyalip Arab Saudi menjadi produsen migas terbesar dunia.
Minyak serpih, kerap disebut kerogen serpih atau bitumen padat, adalah batuan sedimen berbutir halus yang mengandung kerogen. Campuran senyawa kimia organik ini yang menjadi sumber terbentuknya hidrokarbon cair.
Shale oil didefinisikan sebagai batuan sedimen immature, berbutir halus yang mengandung sejumlah besar material organik spesifik, yaitu alginit dan/atau bituminit. Apabila material ini diesktraksi dengan cara dipanaskan lebih dari 550 derajat Celcius, maka akan menghasilkan minyak mentah bernilai ekonomis.
Soal kehadiran kontrak kerja sama baru, SKK Migas tidak banyak memberikan tanggapan. “Kami ini lembaga pelaksana. Tentu akan mengikuti ketentuan pemerintah,†kata Pelaksana Tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih.
Cukup Dua Skema Kontrak Kerja Migas
Pengamat energi Salis S Aprilian berpendapat belum ada sistem kontrak yang lebih baik dari PSC, dengan skema cost recovery maupun gross split. Keduanya sudah cukup menjadi pilihan para investor.
Isu dasar rendahnya investasi pada sektor hulu migas sebenarnya bukan karena kebijakan fiskal. Namun, ketersediaan data, potensi sumber daya alam, dan kepastian hukum.
Apabila tersedia kajian awal yang terpercaya dan akurat, ia meyakini investor akan berhitung lebih cermat. “Apakah mereka akan menganut cost recovery atau gross split itu mudah diputuskan,” kata Salis.
Cost recovery adalah pengembalian biaya operasi dari pemerintah untuk kontraktor migas. Perhitungan biayanya dimulai saat penemuan cadangan migas hingga berproduksi secara komersial.
Pada 2016, alokasi cost recovery terbesar untuk mendukung aktivitas produksi. Angkanya mencapai 49,9% atau sebesar US$ 5,8 miliar. Secara nominal biaya ini turun dibandingkan realisasi 2015 yang mencapai US$ 6,89 miliar. Sedangkan untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan sebesar 15,6%.
Sedangkan gross split, perhitunganya sudah di muka sehingga biaya operasi menjadi beban kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Negara mendapatkan bagi hasil migas dan pajak lebih pasti.
Untuk pengembangan blok migas nonkonvensional perlu ada tambahan aturan karena menyangkut lahan yang luas, sumur produksi yang kecil tapi banyak, dan overlap dengan area operasi existing. “Tapi tetap saja harus diturunkan dari aturan-aturan PSC yang ada, hanya perlu modifikasi,” ucap Salis.
Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto pun berpendapat bentuk kontrak tak menentukan datangnya investasi baru. Yang lebih penting adalah budget dan prioritas portofolio investasi para investor.
Faktor lainnya yang mendukung adalah iklim investasi dan kemudahannya. “Kepastian hukum dan contract sanctity lebih penting daripada jenis atau bentuknya,†kata Pri.
Untuk investasi yang sudah berjalan, perubahan jenis kontrak dengan memperbaiki parameter fiskal memang akan membantu secara keekonomian.
“Namun, mengubah-ubah kontrak juga memberikan sinyal kurang positif terhadap kepastian hukum Indonesia,” ujarnya. Investor memiliki preferensi tentang operasional migasnya.
“Kalau geological reward-nya besar, risiko dan modalnya dapat mereka kelola, serta pemerintah berperan sebagai fasilitator yang baik, maka pasti berhasil,†ucap Pri.
Blok Migas Non Konvensional Masih Berisiko Tinggi
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan pengembangan blok migas nonkonvensional merupakan bisnis marginal.
Di Indonesia masih sangat baru dan membutuhkan banyak trial and error serta fleksibilitas dalam pengadaan teknologi. Pengembangan blok migas yang memiliki risiko tinggi, tentu membutuhkan fleksibilitas. “Termin kontrak yang ada sekarang tidak mampu mendukungnya,†kata Moshe.
Praktisi sektor hulu migas Tumbur Parlindungan pun menyebut perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan daya tarik blok migas nonkonvensional. “Isu utamanya tidak hanya masalah rezim fiskal tapi infrastruktur dan perusahaan penunjangnya,†ucapnya.
Hal serupa juga disampaik pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhi. Fleksibilitas kontrak tidak akan berdampak signifikan mendongkrak investasi. “Di AS, investor diberikan berbagai kemudahan, seperti insentif dan ketersediaan infrastruktur,†ujarnya.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM berencana melelang 10 wilayah kerja (WK) migas pada 2021. Proses pelelangan ini sempat tertunda pada tahun lalu karena Covid-19. Investor nantinya dapat memilih jenis kontrak untuk mengembangkan wilayah kerja migasnya, yaitu cost recovery atau gross split. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Mustafid Gunawan mengatakan langkah ini untuk mendongkrak investasi di sektor tersebut.
Kesepuluh blok migas yang rencananya akan ditawarkan tersebut terdiri dari lima wilayah kerja migas reguler dan lima wilayah kerja hasil studi bersama. Secara total, potensi sumber daya dari 10 wilayah kerja itu mencapai 3,4 miliar barel minyak dan lima triliun kaki kubik gas. Untuk penawaran secara reguler terdiri dari:
1. WK Merangin III yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Jambi (di darat atau onshore).
2. WK Sekayu yang berlokasi di Sumatera Selatan (onshore).
3. WK North Kangean berlokasi di Jawa Timur (di laut atau offshore).
4. WK Cendrawasih berlokasi di Papua (offshore).
5. WK Mamberamo berlokasi di Papua (onshore dan offshore).
Berikutnya, untuk wilayah kerja yang ditawarkan secara langsung terdiri dari:
1. WK West Palmerah yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Jambi (onshore).
2. WK Rangkas yang berlokasi di Jawa Barat dan Banten (onshore)
3. WK Liman berlokasi di Jawa Timur (onshore).
4. WK Bose berlokasi di NTT (onshore dan offshore)
5. WK Maratua II yang berlokasi di Kalimantan Utara (onshore dan offshore).
Katadata.co.id; 22 Februari 2021
Penulis: Komaidi Notonegoro
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute
Hampir dapat dipastikan Indonesia akan memainkan peran penting dalam industri nikel global, termasuk industri nikel untuk baterai mobil listrik.
Momentum pengembangan mobil listrik yang terus menguat berpotensi memberikan dampak positif terhadap industri nikel di Indonesia. Hal tersebut terkait dengan pemanfaatan nikel sebagai komponen baterai mobil listrik.
Pemanfaatan nikel sebagai komponen baterai diyakini dapat mendorong biaya produksi mobil listrik kompetitif dengan mobil yang menggunakan BBM. Saat ini, porsi biaya baterai dilaporkan sekitar 40 % dari total ongkos produksi mobil listrik. Karena itu, berkurangnya biaya produksi baterai akan menurunkan biaya produksi mobil listrik secara keseluruhan.
Saat ini terdapat tiga jenis baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik, yaitu Nickel Cobalt Aluminium (NCA), Nickel Mangan Cobalt (NMC), dan Lithium Iron Phosphate (LFP). Untuk ketahanan panas, baterai jenis NCA memiliki ketahanan panas sekitar 150°C, baterai jenis NMC sekitar 210°C, dan baterai jenis LPF sekitar 270°C. Dari sisi biaya, produksi baterai jenis NCA sekitar US$ 350 per kWh, jenis NMC sekitar US$ 420, dan jenis LPF sekitar US$ 580.  Industri Nikel Indonesia Dari tiga jenis baterai mobil listrik tersebut, biaya produksi baterai yang menggunakan komponen nikel, yaitu NCA dan NMC, tercatat lebih murah dibandingkan yang tidak menggunakan komponen nikel (LPF). Berdasarkan informasi tersebut, selisih biaya produksi antara baterai yang menggunakan nikel dan yang tidak mencapai US$ 70 – 230 untuk setiap kWh-nya.
Industri Nikel Indonesia
Dari tiga jenis baterai mobil listrik tersebut, biaya produksi baterai yang menggunakan komponen nikel, yaitu NCA dan NMC, tercatat lebih murah dibandingkan yang tidak menggunakan komponen nikel (LPF). Berdasarkan informasi tersebut, selisih biaya produksi antara baterai yang menggunakan nikel dan yang tidak mencapai US$ 70 – 230 untuk setiap kWh-nya.
Dapat dikatakan bahwa pemanfaatan nikel merupakan bagian penting untuk menurunkan biaya produksi baterai dan mobil listrik secara keseluruhan. Karena itu, negara-negara yang memiliki cadangan nikel terutama Indonesia akan memainkan peran penting dalam rantai pasok industri baterai maupun mobil listrik secara keseluruhan. Indonesia yang memiliki cadangan nikel sekitar 52 % dari cadangan dunia akan menjadi penentu industri mobil listrik, kompetitif atau tidak dibandingkan mobil berbahan bakar minyak.
Dengan porsi cadangan tersebut, produksi nikel Indonesia dilaporkan sekitar 800 ribu ton atau sekitar 30 % dari total produksi nikel dunia. Saat ini kebutuhan nikel dalam negeri sekitar 30 ribu ton per tahun.
Selama ini sekitar 770 ribu ton atau 96 % dari total produksi nikel Indonesia diperuntukkan bagi pasar ekspor. Selain Indonesia, produsen nikel utama dunia adalah Filipina dan Rusia. Produksi nikel Filipina sekitar 420 ribu ton, sementara Rusia sekitar 270 ribu ton.
Dengan menguasai 52 % cadangan dunia tersebut, hampir dapat dipastikan Indonesia akan memainkan peran penting dalam industri nikel global termasuk dalam hal ini industri nikel untuk baterai mobil listrik. Keberatan Uni Eropa terkait keputusan Indonesia yang melakukan moratorium ekspor nikel semakin menegaskan bahwa Indonesia memainkan peran penting tersebut.
Untuk konteks dalam negeri, industri nikel juga memegang peran penting dalam industri mineral Indonesia secara keseluruhan. Porsi investasi industri pengolahan atau pemurnian nikel yang relatif besar menegaskan bahwa industri nikel menjadi salah satu yang penting.
Sampai 2024, Indonesia menargetkan akan menyelesaikan 53 proyek pembangunan smelter yang mana 30 smelter atau 57 % di antaranya untuk pemurnian nikel. Nilai investasi 53 smelter tersebut sekitar US$ 21,59 miliar, dan US$ 8 miliar dialokasikan untuk mebangun smelter nikel.
Meskipun secara keseluruhan positif, saya menilai masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan dunia usaha terkait pengembangan industri nikel yang dimanfaatkan untuk baterai mobil listrik.
Dari aspek teknis, nikel yang digunakan untuk baterai mobil listrik memerlukan smelter dengan metode high pressure acid leaching (HPAL). Karena itu menjadi logis jika sampai akhir 2020 sedang dibangun empat smelter nikel cobalt dengan metode HPAL di Indonesia, tepatnya di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Untuk membangun pabrik baterai, secara umum akan memerlukan pasokan bahan baku yaitu berupa mix hydroxide precipitate (MHP) maupun mix sulphide precipitate (MSP). Produk tersebut merupakan bahan baku nickel sulphate atau cobalt sulphate yang akan menjadi bahan baku komponen baterai.
Untuk saat ini, di dunia terdapat beberapa smelter yang menggunakan metode HPAL untuk mengolah bijih nikel kadar rendah. Sejumlah informasi menyebutkan pengolahan bijih nikel dengan metode HPAL mempunyai beberapa kendala antara lain biaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan mengolah Nickel Pig Iron (NPI). Karena itu, terkait tekno-ekonomi, terdapat kendala bijih nikel yang diolah harus memiliki kandungan silikat (Si) di bawah 10 % sehingga menjadi tidak ekonomis apabila terus diproduksi.
Kendala dalam tekno-ekonomi pada kegiatan operasi produksi nikel untuk baterai mobil listrik salah satunya direfleksikan dari penutupan sejumlah smelter nikel yang menggunakan metode HPAL. Smelter metode HPAL yang berhenti kegiatan operasinya di antaranya smelter Bulong milik Resources perusahaan di Australia dengan kapasitas produksi 7.000 ton Ni/tahun dan smelter Cawse milik Centaur perusahaan di Australia berkapasitas produksi 9.000 ton Ni/tahun.
Selain masalah tekno-ekonomi, ketersedian regulasi sebagai payung hukum dalam kegiatan operasi produksi perlu menjadi perhatian pemerintah. Terkait kebijakan pengaturan harga, pemerintah cukup progresif. Salah satunya tercermin dari dibentuknya Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel yang telah melaksanakan tupoksinya dengan baik. Pembentukan Tim Kerja tersebut merupakan implementasi Permen ESDM No.11/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM No.7/2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.
Meskipun secara umum kegiatan produksi nikel dapat mengacu pada UU Minerba No. 3/2020, Permen ESDM No. 25/2018 jo Permen ESDM No. 11/2019, dan Permen ESDM No. 25/2018 jo. Permen ESDM No. 11/2019, saya menilai pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang secara khusus mengatur pemanfaatan nikel untuk industri baterai. Apalagi, pengaturan industri baterai kendaraan listrik melalui Perpres No. 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan terpantau masih bersifat cukup makro.

CNBCIndonesia, 17 Februari 2021
Jakarta, CNBC Indonesia –Â Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan jajaran Dewan Direksi dan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia atau Indonesia Investment Authority (INA) kemarin, Selasa (16/02/2021).
Dewan Pengawas diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara untuk posisi CEO diserahkan kepada Ridha DM Wirakusumah yang sebelumnya adalah Direktur Utama PT Bank Permata Tbk (BNLI).
Langkah INA diawali dengan suntikan modal dari pemerintah sebesar Rp 15 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Sri Mulyani mengharapkan modal LPI bisa mencapai Rp 75 triliun di akhir 2021.
Adapun dana LPI ini nantinya ditargetkan untuk membiayai pembangunan nasional, termasuk proyek infrastruktur nasional, salah satunya jalan tol.
Lalu, bagaimana dengan wacana Dana Migas atau Petroleum Fund yang beberapa tahun lalu sempat mengemuka? Apakah masih ada kemungkinan RI untuk memberlakukan Petroleum Fund ini?
Pri Agung Rakhmanto, akademisi perminyakan dari Universitas Trisakti dan juga pendiri ReforMiner Institute, mengatakan pemberlakuan Petroleum Fund di Indonesia tidak akan berjalan mudah dan bisa memakan waktu lama, terutama karena harus dimatangkannya terlebih dahulu konsep, fungsi dan tujuan dari Petroleum Fund ini.
Menurutnya, Petroleum Fund ini berbeda dari penerapan LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) karena SWF ini mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pemerintah, baik dari regulasi payung hukum maupun perangkat organisasi kelembagaannya. Seperti diketahui, landasan pembentukan LPI ini telah diakomodir dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Sementara Petroleum Fund masih terbatas wacana untuk diatur di dalam Revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
“Yang jelas, dalam hal keseriusan, beda jauh antara Petroleum Fund dengan SWF. SWF sudah full dukungan dan komitmen pemerintah, langsung oleh Presiden, dan sekarang sudah mulai diimplementasikan, baik regulasi payung hukum maupun perangkat organisasi kelembagaannya. Petroleum Fund….masih sangat-sangat jauh. Petroleum Fund bisa penting bisa tidak, tergantung konsep dan fungsinya akan ditujukan untuk apa,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (17/02/2021).
Terlebih, lanjutnya, Revisi UU Migas ini tidak dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021, sehingga besar kemungkinan ini belum akan dibahas pada tahun ini.Dia memperkirakan regulasi tentang Petroleum Fund ini akan dimasukkan di dalam Revisi UU Migas nantinya. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai konsep, fungsi, mekanisme, pengelolaan dan hal-hal detail teknis lainnya.
“Ya tentang Petroleum Fund kemungkinan akan masuk ke dalam Revisi UU Migas.. Revisi UU Migas sendiri juga di tahun 2021 ini tidak masuk Prolegnas, sehingga untuk saat ini relatif sulit atau belum bisa dipetakan akan seperti apa Petroleum Fund yang pernah disebut itu nantinya,” tuturnya.
Namun demikian, dia meyakini Petroleum Fund ini bermanfaat bagi pendanaan proyek migas, seperti bisa dialokasikan untuk investasi awal eksplorasi, riset pengembangan sumber-sumber migas baru, infrastruktur migas, dan juga untuk stok ketahanan energi nasional.
“Nah, itu semua, belum jelas di kita. Satu lagi yang juga belum jelas, sumber dananya dari mana. Jika dari sebagian penerimaan migas yang disisihkan, maka itu juga perlu regulasi payung hukum lainnya, di luar UU Migas itu sendiri, karena berkaitan dengan APBN, penerimaan dan keuangan negara,” jelasnya.

Newsetup-Kontan.co.id; 11 Februari 2021
KONTAN.CO.ID -Â JAKARTA. Prospek minyak serpih (shale oil) atau shale hydrocarbon (oil and gas) di Indonesia dinilai cukup besar dan potensial untuk dikembangkan. Pemerintah pun menyatakan bakal menggarap shale oil untuk mencapai target 1 juta barel pada 2030.
Praktisi hulu migas Tumbur Parlindungan mengatakan, meski memiliki potensi yang besar, namun belum ada kajian yang serius untuk mengembangkan shale hydrocarbon di Indonesia. Padahal, shale dapat menjadi penunjang produksi migas jika digarap dengan serius.
Dia mencontohkan, yang memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah di Lapangan Rokan – Sumatera dan Sanga-sanga di Kalimantan. Hal itu dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur baik berupa jalan maupun pipa migas.
“Yang dibutuhkan adanya research dan uji coba untuk melakukannya dengan dibantu ecosystem service company yang memadai atau siap untuk beroperasi,” turur Tumbur yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Indonesian Petroleum Association (IPA) tersebut.
Tantangan utama yang dihadapi ialah terkait rezim fiskal. Tumbur bilang, rezim fiskal saat ini hanya untuk migas konvensional. “Sedangkan setahu saya, untuk unconventional seperti shale belum ada,” sambungnya.
Secara keseluruhan, Tumbur menegaskan bahwa iklim investasi di sektor migas perlu diperbaiki. Selain rezim fiskal, konsistensi menjaga kesucian kontrak (contract sanctity) juga masih menjadi sorotan.
Berkaca dari negara lain, shale hydrocarbon sangat prospektif. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, shale production menjadikan Negeri Paman Sam itu sebagai negara pengekspor minyak. Sebelum ada shale revolution, AS harus melakukan impor migas mendekati level 5 juta barel oil per day (BOPD).
Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Migas dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto. Yang terpenting, dia mengingatkan bahwa pengembangan shale oil/hydrocarbon perlu waktu dan mesti konsisten.
Pasalnya, AS memulai program shale oil dengan riset panjang sejak 1970-an ketika embargo minyak dari timur tengah. Lalu, shale oil di AS mulai berproduksi komersial secara masif baru pada tahun 2000-an awal. “Jadi perlu waktu dan konsistensi. Meski tak berarti akan sama 30 tahun (pengembangan shale hydrocarbon) karena sekarang teknologi untuk mengekstraksinya sudah ketemu, yaitu fracturing,” terang Pri.
Dia menegaskan, perlu investasi eksplorasi skala besar untuk bisa memastikan dan mengubah potensi sumber daya (resources) yang ada menjadi proven reserve.Saat ini yang ada baru berupa potensi sumber daya yang belum teridentifikasi dengan jelas. “Kalau tetap hanya berupa sumber daya, tidak akan berarti apa-apa,” sambung Pri.
Untuk itu, diperlukan iklim investasi yang kondusif untuk bisa menarik minat investor. Apalagi di tengah situasi kompetisi migas global yang ketat. “Negara-negara lain seperti Argentina, Tiongkok, dan wilayah lainnya di Amerika Latin sudah jauh lebih siap dalam hal pengembangan shale oil dibanding kita. Jadi, lebih mudah bagi investor menanamkan investasinya di sana,” jelas Pri.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan bahwa kajian dan eksplorasi mutlak diperlukan jika pemerintah serius ingin mengembangkan shale oil. “Satu-satunya cara harus dieksplorasi dulu untuk melihat prospeknya, tidak ada cara lain,” pungkas Marjolijn.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan, dalam pengembangan migas non konvensional Pemerintah telah melakukan identifikasi potensi shale oil dan shale gas. “Sementara ini kita perlu banyak minyak, jadi kita fokuskan ke shale oil,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang disiarkan di situs resmi Ditjen Migas, Kamis (4/2).
Secara teori, sambung Tutuka, apabila terdapat reservoar minyak di suatu tempat, pasti ada “dapur”. Inilah yang dikejar Pemerintah. “Dapur itu sudah diketahui tempatnya di mana. Dapurnya namanya non konvensional. Kita sudah petakan di mana tempatnya dan kita mau fokus ke satu tempat (shale oil),” tambah Tutuka.
Menurutnya, potensi shale oil Indonesia terbilang cukup besar. Hal ini yang membuat Pemerintah optimis untuk terus berupaya mencapai produksi minyak 1 juta barel pada tahun 2030.

Lokadata.co.id, 11 Februari 2021
Kebutuhan gas LPG bersubsidi terus meningkat dalam lima tahun ini. Hal ini karena gas untuk masyarakat tidak mampu ini banyak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Padahal pemerintah harus mengimpor liquefied petroleum gas ini dan volumenya terus meningkat.
Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Soerjaningsih mengatakan skema penyaluran LPG 3 kg subsidi untuk tahun ini belum akan berubah. Artinya masih menggunakan pola subsidi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Yang pasti keputusan di tahun 2021 kita masih menggunakan pola subsidi yang lama,” ujar Soerja yang juga menjabat sebagai Plt. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Kamis (11/2/2021).
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, volume impor LPG baik untuk subsidi maupun non-subsidi diprediksi 7,2 juta metrik ton (MT) atau naik 16,13 persen dibandingkan dengan realisasi impor pada 2020 yang mencapai 6,2 juta MT.
Nicke mengatakan, Pertamina masih mengimpor LPG lantaran produksi dalam negeri tidak cukup. Saat ini produksi LPG nasional masih berkisar 995 ribu MT dari kilang domestik dan 1 juta MT dari kilang Pertamina.
Kabar baiknya, produksi kilang domestik dan Pertamina naik sehingga impor LPG bisa ditekan. “LPG produksi dalam negeri juga ada peningkatan baik dari kilang Pertamina maupun kilang lain di domestik sehingga kita bisa sedikit mengurangi yang seharusnya diimpor,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (9/2/2021).
Merujuk data Pertamina, sepanjang 2020, produksi LPG dari kilang dalam negeri baru 930.234 MT. Pada 2021 ini, Pertamina memproyeksikan produksi LPG dapat digenjot menjadi 995.814 MT.
Direktur Pertamina Trading dan Komersialisasi, Mas’ud Khamid mengungkapkan, peningkatan laju penjualan LPG subsidi 3 kg dalam lima tahun terakhir sejalan dengan tingkat laju pertumbuhan majemuk tahunan atau compound annual growth rate (CAGR) sebesar 5,3 persen.
Mas’ud mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang terus mendorong pertumbuhan konsumsi LPG bersubsidi setiap tahunnya. Pertama, hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan program konversi BBM kepada LPG.
Setiap tahun Pertamina mendistribusikan converter kit kepada nelayan dan petani untuk dapat beralih ke LPG. Dengan jumlah paket yang diberikan mencapai 25.000 hingga 35.000 paket tiap tahunnya, hal ini ditengarai juga menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan konsumsi.
Kedua, Masud mengungkapkan, sejak 2007 saat awal program konversi minyak tanah ke LPG dilakukan hingga tahun 2020 belum ada perubahan harga LPG subsidi 3 kg. Hal ini kemudian berdampak pada gap antara LPG subsidi dan LPG non subsidi sebesar Rp 5.368 per kg. Padahal, Mas’ud mengungkapkan tren CP Aramco terus mengalami fluktuasi pergerakan harga.
Terakhir, yang tidak kalah penting, tidak adanya kriteria penerima LPG subsidi yang jelas dalam regulasi membuat penyaluran tabung melon ini terus meningkat dan rentan tidak tepat sasaran.
“Dari regulasi yang ada selama ini juga belum ada penegasan kriteria konsumen yang berhak mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi dan berapa besaran jumlah subsidi yang dapat diterima,” katanya.
Perlu perbaikan skema
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai, peningkatan volume konsumsi LPG akibat penambahan wilayah konversi khususnya terkait program converter kit untuk nelayan dan petani merupakan hal yang wajar.
Menurutnya, problem utama dalam peningkatan konsumsi LPG bersubsidi terletak pada skema distribusi yang masih bermasalah. Sampai saat ini, praktik subsidi gas melon yang tidak tepat sasaran masih banyak ditemukan di masyarakat.
Oleh sebab itu, ia lantas mendesak agar pemerintah segera melakukan kebijakan subsidi tertutup untuk LPG 3 kg. “Selama masih dengan skema terbuka maka masih akan ada potensi deviasi. Karena kita tidak pernah tahu berapa sih kebutuhan riil untuk LPG subsidi,” katanya kepada Lokadata.id, Kamis (11/2/2021).
Komaidi menyayangkan terkait masih belum adanya kepastian mengenai pelaksanaan subsidi tertutup untuk LPG 3 kg. Padahal dikatakannya, wacana perubahan skema subsidi langsung ke penerima ini sudah bergulir dalam beberapa tahun terakhir.
Ihwal basis data penerima subsidi LPG, pemerintah dapat menggunakan sejumlah data yang sudah ada sembari diperbarui ketika mulai berjalan ketimbang membuat basis data baru yang lebih sulit dan memakan waktu lebih banyak.
Sejumlah data yang dapat dijadikan acuan menurutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hingga data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Jadi bisa digunakan basis data yang ada, apalagi di tengah pandemi ini pemerintah juga sudah menyalurkan bansos, data tersebut bisa dipakai. Dengan distribusi tertutup akan baik untuk semua pihak, terutama beban anggaran subsidi menjadi lebih jelas peruntukannya,†katanya.
Jika basis data yang digunakan sudah benar, Komaidi mengatakan, ada sejumlah opsi mekanisme subsidi yang dapat dilakukan pemerintah. Misalnya, dengan menerapkan satu harga di pasaran dan penerima manfaat diberikan subsidi dalam bentuk anggaran langsung ke rekening masing-masing.
Ataupun dengan menggunakan kartu khusus agar penjualan LPG bersubsidi tidak salah sasaran lagi. Ia mengatakan, kedua cara ini menekankan pada pemberian subsidi yang menyasar langsung pada penerimanya dan bukan pada komoditas seperti yang terjadi saat ini.
Potensi penyimpangan pada skema tertutup dinilai Komaidi jauh lebih mudah untuk ditangani ketimbang subsidi melalui harga komoditas LPG 3 kg. “Karena kontrolnya akan jauh lebih mudah. Meskipun tidak memakai basis digital, data penerima jauh lebih detail. Apalagi kalau pakai digital akan lebih memudahkan,” tuturnya.
Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Soerjaningsih, mengatakan, perubahan skema subsidi gas melon seperti yang diusulkan oleh Komaidi masih menjadi pembahasan di tingkat kementerian. Ia pun mengaku belum bisa memastikan kapan pembahasan itu akan rampung dan penyaluran LPG subsidi bisa berubah agar lebih tepat sasaran.
“Saat ini sedang dalam proses pembahasan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan mohon bersabar,”kata